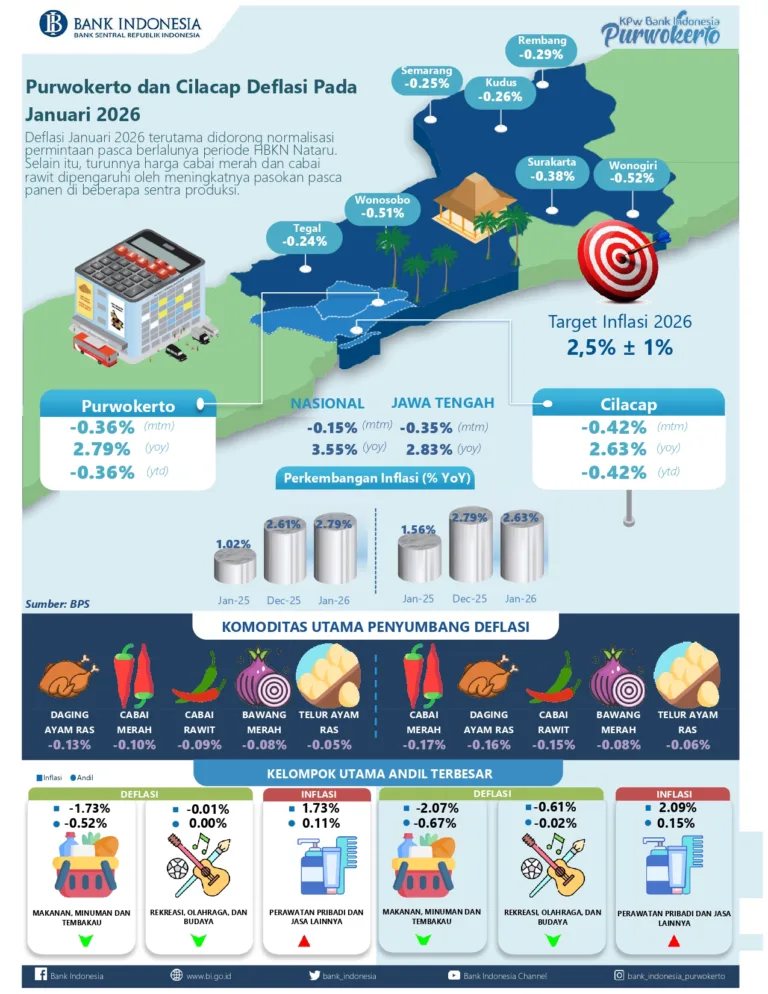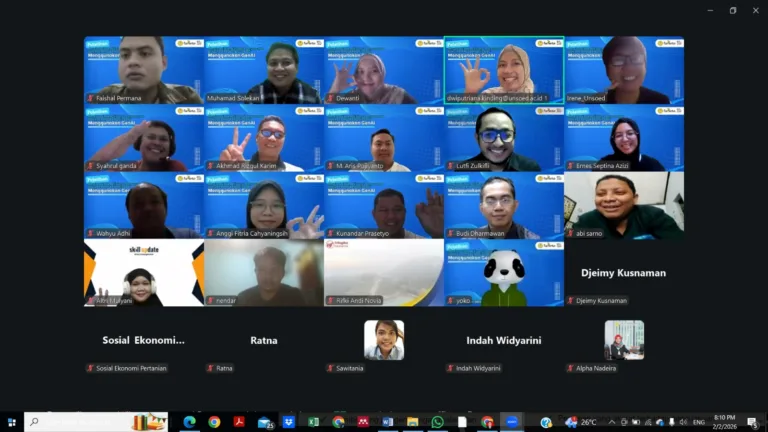Koneksi jalur pemandu ( guiding block) yang terputus oleh kepentingan lain
Koneksi jalur pemandu ( guiding block) yang terputus oleh kepentingan lain
YOGYAKARTA, EDUKATOR--Bagi sebagian orang, jalur pemandu di trotoar hanyalah barisan ubin kuning. Namun bagi penyandang tunanetra, setiap pola di atas lantai itu adalah “peta” menuju kemandirian. Karena itu, kesalahan sekecil apa pun dalam desainnya bisa berakibat fatal.
Di Yogyakarta, pembangunan jalur pemandu telah dimulai sejak 2012, bersamaan dengan pemeliharaan trotoar di sejumlah kawasan kota. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta, Umi Akhsanti, S.T., M.T., menyebutkan bahwa hingga tahun 2025, panjang total trotoar dengan jalur pemandu telah mencapai 34.526 meter.
“Penyediaan jalur pemandu sudah mengacu pada SNI 8153:2015 dan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017,” ujarnya. Ia menambahkan, pengawasan dilakukan oleh konsultan teknis dan direksi lapangan, sementara audit dari BPK dan APIP masih sebatas volume pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak.
Namun, pelaksanaan di lapangan tak selalu semulus dokumen perencanaan. Jalur pemandu yang seharusnya menjadi simbol aksesibilitas, justru sering terputus, salah arah, bahkan berujung di tembok atau tiang listrik.
Antara Standar dan Realitas
Ir. Lucia Asdra Rudwiarti, M.Phil., Ph.D., dosen arsitektur Universitas Kristen Duta Wacana, menilai banyak jalur pemandu di Yogyakarta belum sepenuhnya sesuai dengan ISO 23599:2012, standar internasional untuk tactile walking surface indicators.
“Kalau kita lihat kondisi sekarang, masih banyak kekurangsesuaian. Kemenerusan pola arah sering terputus, bahkan kadang membahayakan pengguna,” ungkapnya. Ia menyebut material yang mudah rusak dan minim perawatan menjadi masalah tambahan di iklim tropis lembap seperti Yogyakarta.
Lucia juga menyoroti bahwa desain yang benar tidak hanya soal fungsi, tetapi juga estetika yang menghargai pengguna.
“Jalur pemandu sebenarnya estetis secara visual. Yang membuatnya tampak kacau justru karena fungsi utamanya sering diabaikan atau belum dipahami masyarakat,” tambahnya.
Menurutnya, prinsip universal design sebenarnya sudah diatur dan diupayakan. Namun, tanpa kesadaran publik yang menghargai kebutuhan pengguna difabel, elemen inklusif akan terus terabaikan.
Ketika Jalur Terputus
Dinas PUPKP mengakui bahwa keterbatasan lahan menjadi tantangan terbesar dalam penerapan standar internasional. Banyak trotoar di kota ini memiliki lebar kurang dari satu meter, sehingga sulit menyesuaikan dengan kebutuhan ruang untuk jalur pemandu yang ideal.
Namun di lapangan, tantangan itu tak hanya soal fisik. Bagi pengguna seperti Akbar Ariantono Putra, mahasiswa tunanetra UIN Sunan Kalijaga, permasalahannya jauh lebih kompleks.
“Tidak selalu mulus. Ada yang bagus seperti Malioboro, tapi banyak juga yang semrawut. UNY trotoarnya jelek tanpa garis kuning, UPN berlubang-lubang,” keluh Akbar.
Ia juga menyoroti kurangnya pelibatan difabel dalam proses pembangunan dan evaluasi.
“Saya tidak pernah dilibatkan. Fasilitas seperti ramp, guiding block, atau papan suara itu sering formalitas saja. Pemerintah bilang belum ada anggaran, padahal masalahnya bukan hanya uang. Tapi kemauan untuk mendengar.”
Menurut Akbar, kota yang ramah difabel adalah kota yang sadar bahwa setiap fasilitas publik adalah hak semua warga.
“Toilet, trotoar, halte, semuanya harus dirancang dengan prinsip design for all,” ujarnya tegas.
Kota yang Mau Mendengar
Dari ketiga perspektif, pemerintah, akademisi, dan pengguna, terlihat bahwa pembangunan jalur pemandu di Yogyakarta telah berjalan, tetapi belum berjalan bersama. Regulasi ada, desain dibuat, namun komunikasi antarpihak masih parsial.
Tanpa koordinasi lintas dinas yang efektif dan pelibatan pengguna nyata, jalur pemandu hanya akan menjadi simbol pembangunan yang tampak rapi di atas kertas, tapi tak berpihak di dunia nyata.
Yogyakarta sering disebut kota dengan semangat kemanusiaan yang kuat. Namun di antara jalur pemandu yang terputus, sesungguhnya kita sedang melihat refleksi paling jujur dari arah kebijakan dan nurani sosial kita. Jalur yang tak tersambung bukan sekadar masalah teknis. Ia tanda bahwa percakapan antara kebijakan, pelaksana, dan pengguna belum benar-benar terjadi.
Bagi mereka yang mengandalkan tongkat, setiap ubin bergelombang bisa berarti tantangan baru. Setiap jalur yang berakhir di tiang, tembok, atau lubang drainase, adalah metafora tentang pembangunan yang belum sepenuhnya mendengar. Kota ini tampak inklusif, tapi belum sungguh mengajak semua orang berjalan bersama di ruang yang setara.
Sebagian komunitas mulai bergerak. SIGAB Indonesia dan sejumlah kelompok disabilitas telah mengajukan audit aksesibilitas partisipatif, sebuah model peninjauan lapangan yang melibatkan langsung pengguna difabel untuk menilai kualitas jalur pemandu. Langkah ini pelan, tapi pasti: mengubah arah dari pembangunan untuk, menjadi pembangunan bersama.
Mungkin dari sana, Yogyakarta bisa kembali menata jalurnya—bukan hanya pada trotoar dan ubin kuning, tetapi juga pada cara kita memandang keberagaman manusia. Karena kota yang benar-benar ramah, adalah kota yang memastikan setiap langkah, tanpa kecuali, bisa menyentuh tanah dengan rasa aman dan bermartabat. (Harta Nining Wijaya)
]