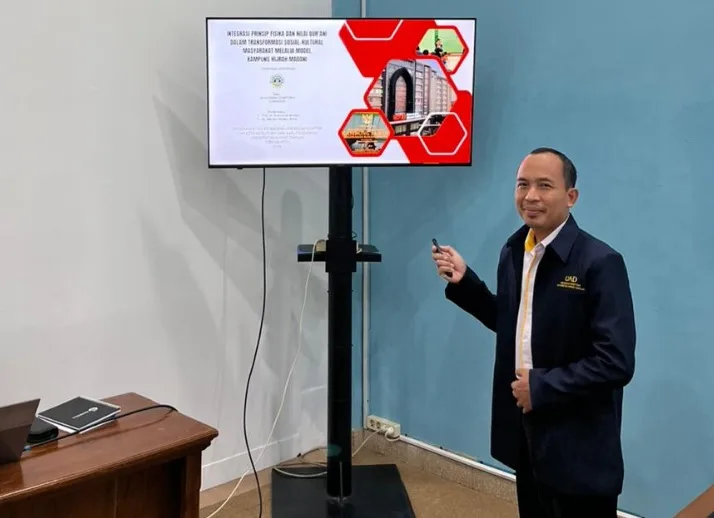*Menembus Batas Ketidakmungkinan

Ashari Sutrisno bersama keluarganya
YOGYAKARTA, EDUKATOR–Di balik setiap langkah kecil yang pelan tapi pasti, ada tangan yang setia menuntun tanpa pamrih. Bagi Ashari Sutrisno, seorang ayah dari anak dengan Cerebral Palsy (CP), pengasuhan bukan sekadar tugas, melainkan panggilan hati. Ia percaya, cinta orang tua bukan diukur dari kesempurnaan anak, tapi dari kesediaan untuk menemani tanpa syarat.
Cerebral Palsy (CP) adalah gangguan pada gerakan, otot, atau postur tubuh akibat kerusakan otak yang terjadi saat otak masih berkembang, biasanya sebelum, saat, atau segera setelah kelahiran.
Kondisi ini bersifat permanen, namun tidak progresif (tidak memburuk seiring waktu). Penderitanya bisa mengalami kesulitan berjalan, koordinasi tubuh terganggu, kejang, atau gangguan bicara dan penglihatan.
CP tidak menular, dan dengan terapi fisik, okupasi, wicara, serta dukungan medis, penyandangnya tetap dapat hidup produktif.
Sejak putranya didiagnosis CP, Ashari mengakui hidupnya berubah arah. Ia tak lagi hanya menjadi pencari nafkah, tetapi juga perawat, pengajar, sekaligus teman bermain. “Dulu saya pikir tugas ayah hanya bekerja, sekarang saya tahu, anak saya butuh saya hadir, bukan hanya kiriman uang,” ujarnya.
Rutinitas Ashari kini berputar di sekitar kebutuhan anaknya. Ia belajar memahami terapi, mencari tahu tentang fisioterapi, dan sabar melatih motorik anaknya di rumah. “Setiap kemajuan kecil bagi anak CP itu besar artinya. Kalau hari ini bisa berdiri lebih lama, itu sudah hadiah,” katanya.
Namun perjuangan Ashari tak selalu mudah. Ia kerap menghadapi pandangan kasihan atau rasa ingin tahu berlebih dari orang lain. Tapi justru dari situ ia belajar arti penerimaan. “Orang tua harus lebih dulu menerima anaknya, baru dunia bisa belajar menerimanya,” ucapnya mantap.
Keterlibatan aktifnya dalam pengasuhan membuat banyak orang di lingkungannya terinspirasi. Ia tak segan datang ke sekolah inklusi, berbicara dengan guru, dan berkoordinasi dengan terapis. Ia juga ikut kelompok dukungan orang tua, tempat ia berbagi cerita dan saling menguatkan.
“Ayah sering dianggap pelengkap. Padahal kalau ayah mau ikut terlibat, dampaknya besar sekali bagi anak.Anak lebih percaya diri, ibu juga lebih tenang, keluarga jadi lebih kuat,” ujarnya.
Di rumah, Ashari berusaha menciptakan ruang aman bagi anaknya. Ia mengajarkan kesabaran lewat permainan sederhana, menghibur ketika anak lelah, dan memberi contoh tentang semangat pantang menyerah. “Saya ingin anak saya tahu, dia tidak sendirian,” katanya dalam sebuah wawancara, Minggu (9/11/2025).
Perjalanan itu membentuknya menjadi sosok yang lebih lembut dan reflektif. Ia mengaku dulu jarang bicara soal perasaan, tetapi kini lebih terbuka. “Anak saya mengajarkan saya untuk mendengar, untuk tidak tergesa-gesa. Kadang, dalam diamnya, dia justru mengajarkan banyak hal,” ujarnya.
Ashari juga menyoroti perlunya dukungan kebijakan yang berpihak pada keluarga dengan anak difabel. Ia berharap pemerintah memperkuat layanan terapi di tingkat desa dan membuka akses pelatihan bagi orang tua. “Kami tidak butuh dikasihani. Kami butuh kesempatan, agar dapat mendampingi anak-anak kami dengan baik,” ujarnya tegas.
Di hari-hari ketika lelah datang, Ashari menemukan kekuatan dalam hal sederhana: senyum anaknya. “Kalau saya lihat dia tersenyum, semua perjuangan itu terbayar,” katanya pelan. “Saya tidak ingin jadi ayah sempurna, cukup jadi ayah yang hadir sepenuh hati,” ujarnya.
Menjelang Hari Ayah, kisah Ashari mengingatkan kita bahwa kasih seorang ayah tak selalu ditunjukkan dengan kata-kata besar, melainkan dengan kesediaan untuk tetap di sana, meski langkah anaknya tertatih. Dalam dunia yang sering lupa menghargai kehadiran ayah, sosok seperti Ashari menjadi bukti bahwa cinta sejati kadang berbicara dalam bahasa paling sederhana: menemani.
Hadir Sepenuh Hati
Kembali ke masa awal hadirnya sang putra. Suara Thoriq dulu nyaris tak terdengar. Ia lahir tergesa, hanya berusia enam bulan dalam kandungan, dengan berat 1,3 kilogram.
Tubuhnya mungil, nyaris tanpa daya, dan harus bertahan di inkubator Rumah Sakit Sardjito selama dua bulan. Saat Ashari Sutrisno dan istrinya akhirnya bisa membopong sang buah hati, tubuh kecil itu masih lemas. Bahkan untuk mendongakkan kepala saja ia tak sanggup.
Dari ruang ke ruang rumah sakit, dari dokter ke dokter, Ashari menapaki perjalanan panjang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hasil CT scan menunjukkan adanya gangguan pada otak, dan kemudian, melalui perjalanan berliku, barulah ia tahu: anaknya adalah penyandang Cerebral Palsy (CP). Sebuah kenyataan yang sempat membuat dunia mereka runtuh.
Awalnya, dokter menduga Thoriq mengalami leukodistrofi, kelainan langka yang menyerang sistem saraf. Ashari terhenyak ketika membaca di internet bahwa penyakit itu bisa membuat anak yang semula normal kehilangan kemampuan motorik dalam waktu singkat.
“Rasanya dunia runtuh,” kenangnya. Namun kebingungan itu mulai terurai ketika ia bertemu Prof. Dr. Sunartini, dokter yang menyatakan dengan pasti bahwa Thoriq mengalami Cerebral Palsy akibat infeksi TORCH (Toxoplasma, CMV, dan Rubella).
Sejak saat itu, Ashari dan istrinya menapaki dua jalur: pengobatan medis di rumah sakit dan terapi alternatif herbal di klinik Pak Juanda. “Kami tidak ingin berhenti hanya pada obat-obatan kimia,” ujarnya. Dari pengobatan alternatif itulah mereka juga mendapatkan pengetahuan baru tentang virus, kekebalan tubuh, dan bagaimana mengelola stres selama mendampingi anak.
Lahirnya Komunitas WKCP
Dari seminar tentang CP yang diikutinya, Ashari bertemu para orang tua dengan kisah serupa. Atas saran Dr Adi Adinugroho, mereka membentuk Wahana Keluarga Cerebral Palsy (WKCP). Komunitas yang kini menjadi ruang belajar dan saling menguatkan. “Di sinilah kami belajar banyak hal: fisioterapi, gizi, psikologi, hingga pendidikan inklusi,” tutur Ashari.
Pertemuan bulanan WKCP tak hanya memperkaya wawasan medis, tapi juga mempererat solidaritas. Para orang tua saling berbagi strategi, saling mengingatkan jadwal kontrol, bahkan saling menjemput untuk terapi bersama. “Kami merasa tidak sendirian lagi,” katanya.
Peran Ashari sebagai ayah berjalan seiring dengan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Ia bekerja penuh waktu, tetapi setelah pukul sembilan malam, ia mengambil alih tugas pengasuhan dari istrinya. “Biasanya Thoriq baru bisa tidur jam tiga atau empat pagi,” katanya lembut.
Ia memandikan, memberi makan, mengganti pampers, bahkan menstimulasi penglihatan anaknya yang semula tidak dapat melihat. Ia lakukan dengan senter kecil, menyorot cahaya ke arah mata Thoriq. Dengan harapan kecil, suatu hari putranya bisa mengenali dunia di sekelilingnya. Harapan itu terwujud perlahan. Dari jarak beberapa sentimeter, hingga akhirnya Thoriq mampu menatap benda-benda di kejauhan. “Sekarang dia bisa melihat jauh, itu luar biasa bagi kami,” ujarnya, senyumnya merekah penuh syukur.
Belajar Hidup ‘Normal’
Ashari pernah berpikir bahwa memiliki anak difabel berarti harus menyerahkan seluruh waktu dan perhatian hanya untuk anak itu. Namun ia segera sadar bahwa keseimbangan adalah kunci. “Kami sempat lalai pada anak pertama, bahkan lupa pada diri kami sendiri,” ungkapnya.
Ia dan istrinya kemudian membagi peran secara proporsional. Mereka tetap bekerja, bersosialisasi, dan berlibur bersama anak-anak. “Keluarga kami harus tetap hidup normal,” tegasnya.
Keyakinan itu membuat mereka tetap utuh, tidak larut dalam kesedihan atau merasa berbeda dari keluarga lain.
Thoriq kini berusia 17 tahun. Ia telah melalui perjalanan luar biasa. Dari tak mampu menegakkan kepala hingga kini bisa berpindah tempat dengan berpegangan pada benda di sekitarnya. Ia makan dan minum sendiri, meski dengan caranya sendiri. “Setiap kemajuan, sekecil apa pun, adalah mukjizat,” ujar Ashari penuh haru.
Dari anaknya, ia belajar tentang makna kesabaran dan ikhtiar. Dari pengalaman hidupnya, ia belajar bahwa kekuatan ayah bukan di suara kerasnya, tapi di keteguhan dan konsistensinya menjaga harapan.
Pesan untuk Ayah Lain
Ashari menyadari, banyak ayah yang masih merasa malu atau enggan tampil di hadapan publik bersama anak difabelnya. Ia mengajak mereka untuk keluar dari persembunyian. “Datanglah ke komunitas. Lihat, ada banyak ayah yang juga berjuang. Dari sana, rasa malu akan hilang, berganti menjadi kebanggaan,” katanya.
Ia juga berharap pemerintah memberi perhatian lebih. Di antaranya: menyediakan sekolah khusus CP dengan guru-guru kompeten. Serta, membangun CP Center sebagai pusat informasi dan dukungan bagi keluarga baru yang menghadapi diagnosis serupa.
“Dokter pernah bilang, kami tidak boleh stres, karena anak CP bisa ikut stres,” ucap Ashari menutup kisahnya. Kalimat itu menjadi pegangan hidupnya. Sebagai ayah, ia memilih untuk tetap tersenyum, tetap bekerja, tetap menjadi tumpuan keluarganya.
Ashari Sutrisno mengatakan, menjadi ayah dari anak Cerebral Palsy bukanlah beban. Melainkan sebuah amanah cinta yang menuntun pada keteguhan, kebersyukuran, dan makna hidup yang lebih luas. (Harta Nining Wijaya)