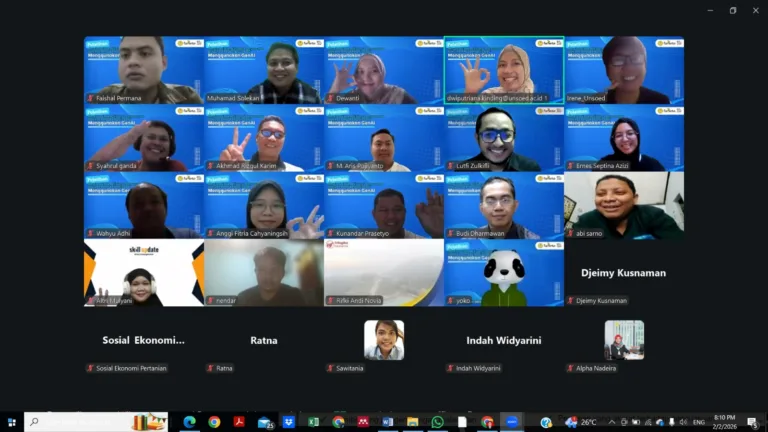Oleh: Priyanto, M.Pd.I
Litbang MKKS SMP Kabupaten Purbalingga
SETIAP bencana di Indonesia selalu menghadirkan dua wajah: luka kemanusiaan dan gelombang solidaritas. Ketika banjir melanda, gempa mengguncang, atau longsor merenggut nyawa, masyarakat bergerak cepat. Bantuan berdatangan, relawan turun ke lapangan, media sosial dipenuhi ajakan donasi. Dalam waktu singkat, empati menjadi bahasa bersama.
Namun, setelah berita mereda, kepedulian pun perlahan surut. Solidaritas yang semula membuncah kembali menjadi rutinitas yang dingin. Di titik inilah kita perlu bertanya: apakah kepedulian sosial kita telah menjadi kesadaran yang terdidik, atau hanya reaksi emosional yang sesaat?
Pertanyaan ini penting karena Indonesia bukan sekadar negeri yang indah, tetapi juga negeri yang rawan bencana. Gempa, banjir, letusan gunung api, dan krisis iklim bukan peristiwa insidental, melainkan bagian dari realitas struktural bangsa. Jika bencana adalah keniscayaan geografis, maka kepedulian harus menjadi keniscayaan pedagogis.
Solidaritas yang Rapuh
Dalam perspektif sosiologi, Émile Durkheim menegaskan bahwa solidaritas sosial adalah fondasi keberlangsungan masyarakat. Solidaritas tidak lahir secara spontan dan bertahan dengan sendirinya; ia dibentuk melalui institusi sosial yang menanamkan nilai-nilai kolektif. Ketika solidaritas tidak dilembagakan, ia akan rapuh—mudah muncul, tetapi cepat menghilang.
Fenomena ini terlihat jelas dalam respons terhadap bencana. Kepedulian sering hadir dalam bentuk bantuan karitatif: donasi, penggalangan dana, dan aksi relawan. Semua itu penting, tetapi belum cukup. Kepedulian yang hanya bersifat karitatif cenderung temporer dan tidak menyentuh akar persoalan.
Di sinilah pendidikan memiliki peran strategis. Pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan ruang pembentukan kesadaran sosial. Tanpa pendidikan yang menanamkan empati secara sistematis, solidaritas akan terus berulang dalam siklus emosional: muncul saat krisis, menghilang saat situasi normal.
Pendidikan sebagai Proses Humanisasi
Paulo Freire mengingatkan bahwa pendidikan sejati adalah proses humanisasi—proses membangun kesadaran kritis tentang realitas sosial. Pendidikan tidak boleh berhenti pada hafalan fakta, tetapi harus mengajak peserta didik memahami penderitaan manusia dan struktur yang melatarinya.
Dalam konteks kebencanaan, pendidikan sering kali terbatas pada pengetahuan teknis: jenis bencana, mitigasi, dan prosedur evakuasi. Pengetahuan ini penting, tetapi tidak cukup. Pendidikan juga harus membentuk kepekaan moral: kemampuan merasakan penderitaan orang lain dan kesediaan untuk bertindak.
Empati bukan sekadar sifat bawaan, melainkan kompetensi yang dapat dilatih. Ia tumbuh melalui pengalaman, refleksi, dan dialog. Ketika peserta didik diajak memahami kisah korban bencana, menganalisis faktor sosial di balik bencana, dan terlibat dalam aksi solidaritas, mereka tidak hanya belajar tentang bencana, tetapi juga belajar menjadi manusia.
Sekolah dan Warga Dunia
Martha Nussbaum, melalui gagasan education for humanity, menekankan bahwa pendidikan harus melahirkan warga dunia yang memiliki empati dan kemampuan berpikir kritis. Pendidikan tidak boleh membatasi peserta didik pada kepentingan diri sendiri atau kelompok sempit, tetapi harus membuka horizon kemanusiaan yang lebih luas.
Dalam konteks Indonesia, gagasan ini menjadi sangat relevan. Bencana bukan hanya persoalan lokal, tetapi juga persoalan kemanusiaan.
Ketika peserta didik memahami bahwa penderitaan korban bencana adalah bagian dari pengalaman manusia secara universal, kepedulian tidak lagi bersifat sporadis, melainkan menjadi sikap hidup.
Sekolah memiliki potensi besar sebagai laboratorium kepedulian sosial. Pembelajaran berbasis proyek dapat mengajak peserta didik mengkaji risiko bencana di lingkungan sekitar, merancang program solidaritas, dan mengembangkan solusi kreatif. Model service learning memungkinkan peserta didik belajar melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan sosial.
Integrasi pendidikan kebencanaan juga perlu dilakukan secara lintas mata pelajaran. Geografi mengajarkan risiko alam, pendidikan agama menanamkan nilai empati, pendidikan kewarganegaraan membangun tanggung jawab sosial, bahasa dan seni menjadi medium ekspresi kepedulian. Dengan cara ini, empati tidak diajarkan sebagai tema tambahan, tetapi menjadi ruh pendidikan.
Dari Empati Viral ke Kesadaran Kritis
Di era media sosial, kepedulian sering kali tampil dalam bentuk “empati viral”. Bencana menjadi tontonan, korban menjadi objek visual, dan solidaritas menjadi konten. Kepedulian semacam ini tidak selalu salah, tetapi rentan menjadi performatif: tampak peduli, tetapi tidak berkelanjutan.
Dalam kerangka Freire, empati viral belum mencapai tahap kesadaran kritis.
Ia belum menyentuh akar persoalan: ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, tata kelola pembangunan, dan kebijakan publik yang sering memperbesar risiko bencana. Pendidikan kepedulian harus melampaui simpati dan masuk ke wilayah refleksi kritis.
Peserta didik perlu diajak memahami bahwa bencana bukan hanya peristiwa alam, tetapi juga peristiwa sosial. Banjir tidak semata-mata akibat hujan, tetapi juga akibat kerusakan hutan dan tata kota yang buruk. Longsor tidak hanya soal geologi, tetapi juga soal kemiskinan yang memaksa orang tinggal di wilayah rawan.
Ketika kepedulian dibangun di atas pemahaman kritis, solidaritas tidak lagi bersifat reaktif, tetapi proaktif. Kepedulian tidak hanya muncul setelah bencana, tetapi juga hadir dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko.
Membangun Ekosistem Kepedulian
Pendidikan kepedulian tidak dapat dibangun secara parsial. Ia membutuhkan ekosistem yang melibatkan sekolah, keluarga, pemerintah, media, dan komunitas. Kurikulum harus memberi ruang bagi pendidikan kebencanaan dan empati sosial. Kebijakan publik harus mendukung program sekolah peduli bencana. Media harus berperan sebagai ruang edukasi, bukan sekadar sensasi.
Dalam perspektif Durkheim, institusi sosial berfungsi menjaga kohesi masyarakat. Ketika pendidikan berhasil menanamkan kepedulian sebagai nilai kolektif, solidaritas tidak lagi bersifat insidental, tetapi menjadi bagian dari identitas bangsa. Di tengah krisis ekologis dan sosial, kepedulian bukan lagi nilai tambahan, melainkan kebutuhan fundamental.
Kepedulian sebagai Takdir Pedagogis
Jika bencana adalah takdir geografis bangsa ini, maka kepedulian harus menjadi takdir pedagogisnya. Pendidikan tidak boleh berhenti pada pencapaian akademik, tetapi harus melahirkan manusia yang peka terhadap penderitaan sesama.
Di sanalah pendidikan menemukan makna terdalamnya: bukan sekadar mencerdaskan, tetapi memanusiakan.
Transformasi dari solidaritas spontan menuju pendidikan kepedulian adalah agenda besar pendidikan Indonesia.
Di tengah luka-luka bencana, pendidikan memiliki peluang untuk membangun generasi yang bukan hanya tangguh secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral. Sebab, pada akhirnya, kualitas sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kecerdasan warganya, tetapi dari kedalaman empatinya.(*)