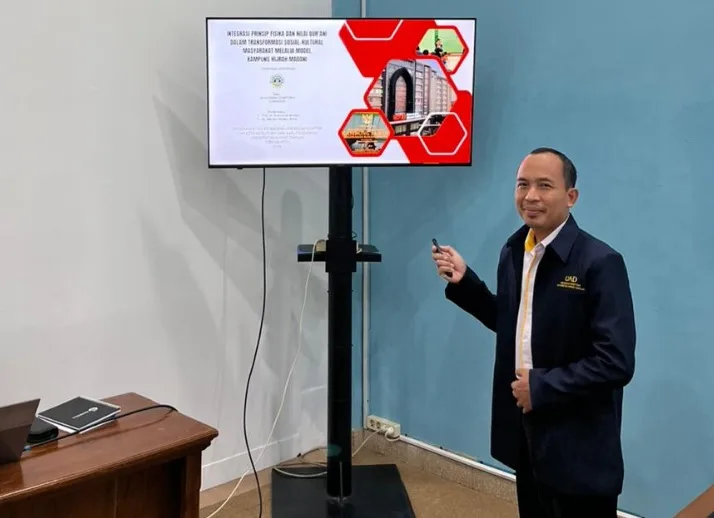Oleh: Drs. Prasetiyo, M.I.Kom
Pemimpin Redaksi Edukator
KONSTITUSI dan undang-undang mengamanatkan dengan tegas: anggaran pendidikan nasional harus mencapai minimal 20 persen dari APBN. Angka itu sudah rutin terpenuhi setiap tahun, termasuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Namun pertanyaannya, apakah anggaran yang besar itu benar-benar menjamin akses pendidikan bagi anak-anak miskin sekaligus kesejahteraan para guru?
Sayangnya, realitas di lapangan masih jauh dari harapan. Anak-anak dari keluarga prasejahtera masih terseok untuk membayar biaya sekolah atau kuliah, meski ada berbagai program bantuan. Sementara di sisi lain, guru dan dosen—para penggerak utama pendidikan—sering kali belum menikmati kesejahteraan yang layak. Inilah kontradiksi yang membuat kita layak bertanya: ke mana larinya alokasi dana pendidikan yang katanya besar itu?
Harian Kompas edisi Jumat 29 Agustus 2025 halaman 5 menurunkan berita berjudul “Susahnya Menjamin Pendidikan Anak Miskin dan Kesejahteraan Pendidik”. Isinya menyoroti bagaimana anggaran pendidikan yang besar ternyata belum cukup untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat.
Program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP Kuliah memang ada, tetapi kuota penerima terbatas. Banyak siswa dari keluarga miskin yang masih kesulitan menutup biaya sekolah dan biaya hidup. Di perguruan tinggi, mahasiswa penerima KIP Kuliah pun hanya bisa terbantu sebagian, sementara realitas ekonomi keluarganya tetap menghimpit.
Di sisi lain, kesejahteraan guru pun tidak lebih baik. Masih banyak tenaga pendidik yang hidup pas-pasan, bahkan harus mencari pekerjaan tambahan. Kritik juga diarahkan ke DPR yang kerap membatasi ruang fiskal untuk memperluas bantuan pendidikan. Harapan agar alokasi pendidikan bisa ditingkatkan hingga 10 persen dari PDB masih jauh panggang dari api.
Ironi yang Tak Pernah Usai
Inilah ironi yang terus berulang: anggaran pendidikan besar, tetapi tidak terasa sepenuhnya di akar rumput. Anak miskin tetap sulit bersekolah, guru tetap sulit hidup layak. Seolah ada tembok tebal antara angka-angka dalam dokumen APBN dengan kenyataan sehari-hari di kelas dan kampus.
Ironi lain terlihat dari retorika pemerintah tentang pentingnya kualitas sumber daya manusia. Kita mendengar jargon “bonus demografi” dan “generasi emas” hampir setiap tahun. Namun ketika berhadapan dengan kebijakan nyata, keberpihakan pada kelompok miskin masih setengah hati. Pendidikan memang digratiskan di atas kertas, tetapi biaya tak langsung—transportasi, buku, gadget, bahkan makan sehari-hari—tetap menghantui keluarga miskin.
Bagi guru, ironi juga nyata. Mereka disebut pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi penghasilan mereka sering tidak cukup untuk menutup kebutuhan dasar. Guru honorer masih tersebar di banyak sekolah dengan gaji jauh di bawah upah minimum. Apakah kita bisa berharap pendidikan bermutu lahir dari pendidik yang hidupnya penuh keterbatasan?
Akar Masalah: Distribusi dan Keberpihakan
Masalah utama bukan semata pada besar-kecilnya anggaran, melainkan pada distribusi dan keberpihakan. Selama ini, sebagian dana pendidikan justru terserap pada pos-pos birokrasi, infrastruktur, atau proyek yang tidak langsung menyentuh siswa dan guru. Akibatnya, anak-anak miskin tetap kesulitan membayar biaya kuliah, dan guru tetap berjuang menghidupi keluarganya.
Lebih jauh, bantuan yang ada sering kali tidak menjangkau semua yang membutuhkan. Mekanisme seleksi penerima KIP Kuliah misalnya, kerap tidak akurat. Ada yang benar-benar miskin tapi tidak terdata, sementara yang relatif mampu justru bisa menerima.
Lalu, bagaimana seharusnya? Ada beberapa langkah yang bisa ditempuh:
1.Reorientasi anggaran pendidikan
Dana pendidikan harus benar-benar diarahkan pada kebutuhan inti: membebaskan anak miskin dari hambatan biaya, dan menyejahterakan guru sebagai tulang punggung sistem. Pos-pos anggaran yang tidak efektif perlu dipangkas, dialihkan ke beasiswa dan insentif bagi pendidik.
2.Perluasan bantuan langsung
Program seperti KIP dan KIP Kuliah harus diperluas, tidak hanya mencakup biaya pendidikan formal, tetapi juga biaya hidup dasar. Karena bagi keluarga miskin, tantangan utama bukan hanya uang kuliah, tetapi ongkos makan, kos, hingga transportasi.
3.Reformasi kesejahteraan guru
Pemerintah harus menata ulang sistem penggajian guru, terutama honorer. Gaji layak adalah syarat mutlak agar guru dapat mengajar dengan tenang. Tanpa itu, mutu pendidikan hanya akan jadi slogan.
4.Pengawasan ketat
Perlu mekanisme transparansi dan partisipasi publik dalam mengawasi distribusi anggaran pendidikan. Tanpa kontrol, dana pendidikan mudah bocor ke proyek-proyek yang tidak jelas manfaatnya.
Pendidikan adalah jalan utama untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi. Namun jika anak miskin tetap sulit bersekolah, dan guru tidak sejahtera, maka misi itu tinggal wacana. Kita tidak boleh membiarkan kontradiksi ini berlanjut.
Bangsa ini hanya akan maju jika keberpihakan pada pendidikan benar-benar nyata, bukan sekadar angka di APBN. Membiayai pendidikan anak miskin dan menyejahterakan pendidik bukanlah beban, melainkan investasi masa depan. Semoga (***)