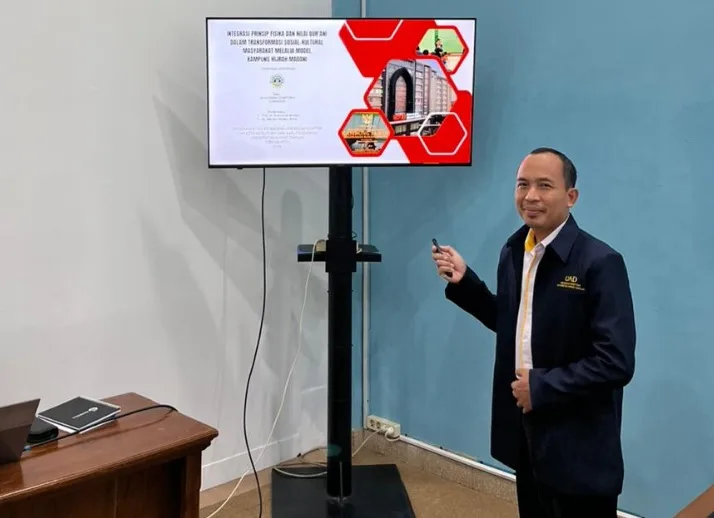YOGYAKARTA, EDUKATOR–Dalam senyap, namun pasti, SMA Bopkri 2 (BODA) Yogyakarta telah membangun praktik pendidikan multikultur yang nyata. Di tengah kecenderungan homogenisasi dan kekhawatiran perbedaan, BODA hadir sebagai ruang aman bagi siapa pun: lintas agama, suku, kondisi sosial, hingga disabilitas. Di sekolah inilah keberagaman bukan hanya jargon. Melainkan nafas kehidupan sehari-hari.
Perbedaan tidak dirayakan dengan seremoni atau slogan, tapi melalui praktik sehari-hari. Dari siswi difabel netra yang belajar mandiri, siswa muslim yang menemukan ruang aman beribadah, hingga guru-guru yang menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan setiap anak.
Angela Electra
Setiap pagi, Angela Electra (17) berjalan memasuki sekolah dengan tongkat putihnya. Tanpa jalur pemandu (guiding block) dan tanpa pendamping tetap, ia menata ritme belajarnya sendiri. “Sejak kelas XI saya sudah full mandiri,” ujarnya.
Ia menjelaskan, lingkungan sangat mendukung. Teman dan para guru membantu kalau ada pelajaran yang banyak visualisasinya. Ada guru yang mengirim materi power point, ada yang menjelaskan lagi lewat WhatsApp. “Semua memudahkan,” tutur Angela, siswi difabel netra.
Angel mengaku tidak pernah mengalami tantangan sosial yang berkaitan dengan ke-disabilitasan-nya. Konflik kecil ada, namun “itu biasa dan bisa diselesaikan”.
Yang ia rasakan justru sekolah yang memanusiakan. Guru-guru bertanya tentang apa yang belum ia pahami. Teman angkatan, lintas angkatan yang spontan menuntun saat ia butuh bantuan. Bahkan mahasiswa PPL yang tanpa diminta hadir untuk menolong.
Makna keberagaman baginya sederhana namun mendalam. “Berbeda itu untuk diekspresikan, bukan disembunyikan. Kita bisa menerima tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing. Beragam itu nyata, dihargai saja biar lebih indah.”

M Rizqy Fajar
Berbeda dengan Angel, perjalanan M. Rizqy Fajar atau Kiki (17) menuju BODA penuh luka. “Saya dulu di-bully sejak SD. Bahkan soal belum bayar uang sekolah, diumumkan di kelas. Malu sekali,” tuturnya.
Karenanya, masuk ke sekolah yang bernaung di bawah Yayasan Kristen BOPKRI itu, menjadi titik balik hidupnya.
Ia mengakui bahwa awalnya ia membawa “dendam dan trauma panjang.” Namun yang ia temui di BODA justru kebalikan dari masa lalunya. Tidak ada penghukuman khusus pada siswa muslim, tidak ada pengumuman soal tunggakan, dan suasana yang lebih manusiawi. Menurut Kiki, ternyata bukan agamanya yang salah, melainkan perilaku manusianya.
Yang paling ia kenang adalah hari ketika ia merasa “menjadi bagian dari sesuatu”:
“Cuma diajak ke kantin aja… itu hal mewah buat saya. Di SD saya tidak pernah diperlakukan sebagai teman.”
Kiki juga membuktikan bahwa kekhawatiran tentang ibadah di sekolah kristen tidak beralasan. “Enam tahun sekolah di yayasan Kristen, gak pernah dipaksa jadi kristen.
“Dulu, saya satu-satunya muslim yang selalu salat di Hotel Kimaya, karena belum ada mushola. Peristiwa ini sampai ke kepala sekolah. Tahun berikutnya sekolah bangun mushola kecil. Itu bentuk multikultur yang nyata, bukan omongan,” ujarnya.
Bukan Program
Bagi para guru, keberagaman bukan sekadar menerima siswa berbeda agama atau difabel. Ia hadir dalam pola pikir, metode mengajar, dan cara berinteraksi.
Seorang guru Bahasa Inggris Gesnita Ardiyani, menuturkan, pada awal mengajar, tahun 2003, pernah menangani siswa bipolar. Ada pula siswa pengguna kursi roda, hingga siswa lambat belajar (slow learner). “Kuncinya mau belajar. Mau menerima. Multikultur itu bukan teori, tapi bagaimana kami menjadikan ruang kelas hidup bagi semua,” katanya.
Model pembelajaran di BODA pun tidak konvensional. Muridlah yang mencari guru, bukan guru yang selalu tinggal di kelas. Pendekatan ini mendorong interaksi setara, dialogis, dan adaptif.
Rumah Dicintai
Kepala sekolah, Yudha Kusniyanto, membawa visi yang tak lazim dalam dunia pendidikan yang kerap mengejar angka dan ranking. “Ketika saya dipercaya memimpin sekolah, saya tidak ingin membuat sekolah seperti yang masyarakat harapkan. Hanya untuk mengejar perguruan tinggi negeri (PTN) atau nilai. Saya ingin membuat sekolah seperti rumah. Rumah yang mencintai anak-anak, dan dicintai anak-anak.”
Ia mengubah banyak hal. Dari durasi jam pelajaran dipersingkat, hari Jumat pulang lebih cepat agar siswa muslim bisa Jumat-an bersama keluarga, pembagian kelompok kelas yang tidak boleh berdasarkan agama atau kepintaran, hingga membuka ruang-ruang ekspresi BODA Creative Week.
Satu minggu penuh pada tiap minggu kelima, para siswa diperbolehkan mengekspresikan diri. Ada yang mengecat rambut, mengenakan tindik di hidung, atau berpenampilan bebas, misalnya. Lalu, para siswa mempresentasikan makna di balik pilihannya. “Saya ingin nilai, bukan sekadar disiplin,” katanya.
Pada kesempatan yang sama Ketua Yayasan BOPKRI, Obed Tri Pambudi, menegaskan, sekolah diberi keleluasaan mengembangkan kekhasannya sendiri. “SMA BODA memilih multikultur sebagai kekhasannya, dan kami mendukung penuh. Mulai dari rencana strategis yayasan sampai program sekolah, semuanya diarahkan agar visi multikultural bisa hidup dalam praktik.”
Agen perubahan
Sedangkan bagi Dr Sri Sulatri, sang penggagas yang juga kepala sekolah SMA BODA periode 2017–2023, multikultural adalah keniscayaan. “Yang kami rancang adalah bagaimana anak-anak di sekolah ini menjadi agen perubahan. Mulai dari cara mereka memandang orang lain, bergerak, berinteraksi, hingga cara belajar mereka.”
Dalam pandangan Sri Sulastri, multikultur bukan hanya agama, budaya, atau intelektual. “Multikultur itu cara pandang, cara berjalan, cara mendengar, cara menerima keberbedaan. Ia harus hidup dalam keseharian mereka.”
Tantangan Tetap Ada
BODA masih dibayangi citra lama sebagai sekolah “keras” di masa lalu. Namun perlahan, dengan praktik yang konsisten, sekolah ini membangun wajah baru. Sekolah yang aman, ramah, dan manusiawi.
Keberagaman di BODA bukan konsep, tetapi nafas harian. Angel yang belajar mandiri tanpa hambatan sosial. Kiki yang menemukan kembali martabat dirinya. Siswa muslim dan kristen yang belajar agama di ruang yang sama damainya.
Guru-guru yang terbuka terhadap perbedaan karakter dan kebutuhan, serta pemimpin yang mendahulukan nilai kemanusiaan di atas formalitas. (Harta Nining Wijaya)