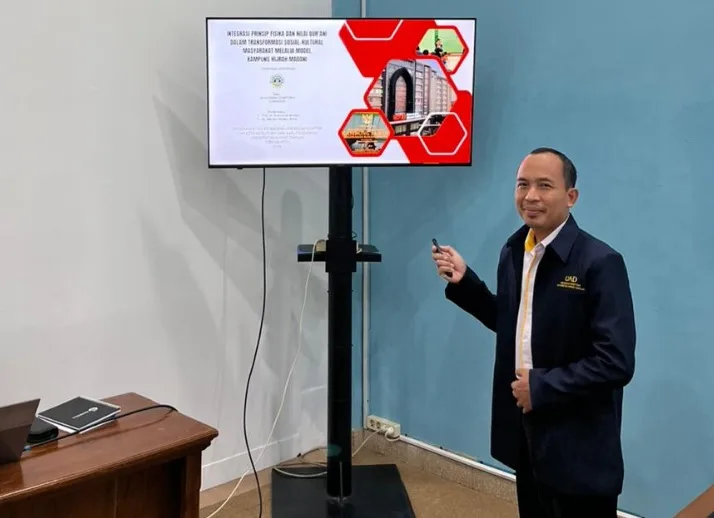Oleh: Priyanto, M.Pd.I
Oleh: Priyanto, M.Pd.I
Kepala SMPN 3 Kutasari dan Plt Kepala SMPN 1 Kutasari
Kabupaten Purbalingga
SETIAP peringatan Isra Mi‘raj Nabi Muhammad SAW, umat Islam diajak kembali merenungkan sebuah peristiwa spiritual yang melampaui logika keseharian. Isra Mi‘raj bukan sekadar kisah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik menembus lapisan langit, tetapi juga narasi tentang iman, kemanusiaan, dan tanggung jawab moral. Pesan inilah yang menjadikan Isra Mi‘raj relevan untuk dibaca ulang dalam konteks pendidikan karakter hari ini.
Nurcholish Madjid, pemikir Muslim Indonesia yang dikenal dengan gagasan Islam substantif, kerap menegaskan bahwa agama sejatinya bukanlah kumpulan simbol atau ritual kosong, melainkan sumber nilai yang membebaskan dan memanusiakan (Madjid, 1997).
Dalam kerangka ini, Isra Mi‘raj dapat dipahami sebagai pengalaman spiritual yang berujung pada amanah sosial. Nabi Muhammad SAW “naik” untuk memperoleh pencerahan, tetapi kemudian “turun” kembali ke bumi untuk menjalankan misi kemanusiaan.
Spiritualitas sejati, dengan demikian, tidak menjauhkan manusia dari realitas, tetapi justru menguatkan keterlibatan etis di dalamnya.
Iman Bukan Sekedar Pengakuan Formal
Pesan tersebut memiliki implikasi penting bagi pendidikan karakter. Iman, menurut Cak Nur, bukan sekadar pengakuan formal, melainkan kesadaran batin yang melahirkan kejujuran, kerendahan hati, dan tanggung jawab sosial (Madjid, 2000).
Pendidikan yang berangkat dari iman semacam ini tidak bertujuan mencetak peserta didik yang patuh secara lahiriah, tetapi pribadi yang luhur akhlaknya—mampu menghargai sesama, bersikap adil, dan menjaga integritas diri.
Dalam konteks Isra Mi‘raj, perintah salat yang diterima Nabi sering dipahami sebatas kewajiban ritual. Padahal, salat juga merupakan latihan karakter: disiplin waktu, kesadaran diri, pengendalian emosi, dan kehadiran batin.
Nilai-nilai ini merupakan fondasi penting bagi pembentukan pelajar yang unggul. Pendidikan karakter yang berakar pada iman tidak melahirkan manusia yang kaku, tetapi pribadi yang seimbang secara spiritual, emosional, dan sosial (Tilaar, 2012).
Bersifat Dinamis dan Progresif
Lebih jauh, iman dalam perspektif Nurcholish Madjid bersifat dinamis dan progresif. Ia tidak mematikan nalar, melainkan mendorong keterbukaan berpikir dan kreativitas. Cak Nur menolak dikotomi antara agama dan kemajuan.
Baginya, iman yang matang justru mendorong manusia untuk terus belajar dan melampaui batas-batas lama (Madjid, 1995). Dalam cahaya ini, Isra Mi‘raj dapat dibaca sebagai simbol keberanian intelektual dan spiritual—keberanian untuk menjelajah kemungkinan baru.
Dalam dunia pendidikan, pesan tersebut sangat relevan. Peserta didik tidak semestinya dibentuk menjadi penghafal pasif, tetapi subjek pembelajar yang kreatif dan reflektif. Kreasi dalam belajar—baik dalam seni, sains, teknologi, maupun pemecahan masalah—bukanlah ancaman bagi religiositas. Sebaliknya, kreativitas merupakan buah dari iman yang sehat, terbuka, dan bertanggung jawab (Robinson, 2016).
Namun, kreativitas yang lahir dari iman juga memiliki orientasi etik. Ia tidak berhenti pada kebaruan atau popularitas, tetapi diarahkan pada kemaslahatan. Di sinilah pendidikan karakter menemukan maknanya: membimbing peserta didik agar mampu berkarya dengan kesadaran nilai. Kreasi bukan hanya soal “bisa”, tetapi juga “bermakna” dan “bermanfaat” bagi lingkungan sosial (OECD, 2019).
Kedalaman Nilai dan Tangungjawab
Adapun prestasi, dalam kerangka pemikiran ini, perlu dimaknai secara lebih utuh. Prestasi tidak semata diukur melalui angka, peringkat, atau piala. Prestasi sejati adalah hasil dari proses pertumbuhan manusia secara menyeluruh—intelektual, emosional, dan moral.
Nurcholish Madjid berulang kali menekankan bahwa kualitas manusia diukur dari kedalaman nilai dan tanggung jawabnya, bukan semata dari capaian lahiriah (Madjid, 2004).
Isra Mi‘raj mengajarkan bahwa pencapaian tertinggi manusia bukan hanya keberhasilan duniawi, tetapi kemampuan menjaga keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan dan tanggung jawab sosial.
Dalam konteks sekolah, ini berarti menciptakan ekosistem pendidikan yang tidak hanya mengejar target akademik, tetapi juga menumbuhkan makna, etika, dan harapan (Senge, 2006).
Sekolah Menjadi Ruang Strategis
Sekolah, dengan demikian, menjadi ruang strategis untuk menghidupkan nilai-nilai Isra Mi‘raj secara kontekstual. Guru bukan sekadar penyampai materi, tetapi pendidik yang menyalakan kesadaran.
Peserta didik bukan objek evaluasi, melainkan subjek yang diajak bertumbuh. Pendidikan karakter tidak cukup diajarkan melalui ceramah, tetapi harus dihidupi melalui keteladanan, dialog, dan budaya sekolah yang manusiawi.
Pada akhirnya, memperingati Isra Mi‘raj dalam dunia pendidikan adalah upaya menghidupkan iman yang membebaskan—iman yang menumbuhkan keluhuran akhlak, menggerakkan kreasi, dan mengarahkan prestasi pada nilai-nilai yang bermakna. Dari sinilah diharapkan lahir generasi pelajar yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga matang sebagai manusia dan warga bangsa. (*)